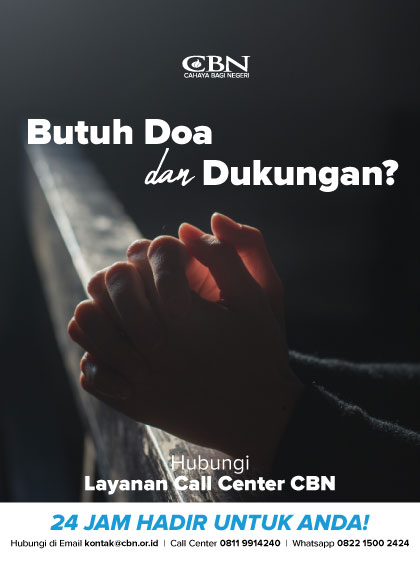Kata Alkitab / 16 August 2007
Pria Berencana Tuhan Tertawa

Admin Spiritual Official Writer
Sebagai orang tua tunggal yang punya hak penuh mengasuh dua anak kecil, hidupku sibuk. Kadang-kadang aku sampai kewalahan. Aku mengajar di universitas, pulang ke rumah, memasak, membersihkan rumah, mencuci, membacakan cerita, dan bermain dengan kedua anakku. Sebagai laki-laki, aku harus belajar mengerjakan semua hal yang biasa dikerjakan kaum wanita.
 Lebih dari itu, karierku sebagai pelatih dan penceramah menanjak secepat roket. Aku diundang berceramah di mana-mana, kesempatan datang berlimpah-limpah. Menyeimbangkan semua tanggung jawab itu membuatku sangat stres. Tapi aku sudah membuat komitmen pada diriku sendiri untuk menjadi yang terbaik. Guru terbaik, penceramah terbaik, dan yang paling penting, ayah terbaik.
Lebih dari itu, karierku sebagai pelatih dan penceramah menanjak secepat roket. Aku diundang berceramah di mana-mana, kesempatan datang berlimpah-limpah. Menyeimbangkan semua tanggung jawab itu membuatku sangat stres. Tapi aku sudah membuat komitmen pada diriku sendiri untuk menjadi yang terbaik. Guru terbaik, penceramah terbaik, dan yang paling penting, ayah terbaik.
Tanggung jawab di tempat kerja sangat membebaniku, dan penghasilan yang terbatas sulit menolak tawaran-tawaran untuk berceramah. Apakah berceramah di perusahaan besar, di sekolah desa, atau di perkumpulan tertentu, nyatanya aku tidak bisa menolak kemungkinan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Ringkasnya, aku selalu sangat sibuk setiap hari.
Waktu itu pagi hari di musim dingin yang khas Cleveland, langit kelabu dan angin dingin menusuk tulang. Aku harus menyiapkan anak-anak sebelum mereka dititipkan ke nursery school (tempat penitipan anak),  memastikan pengasuh mereka datang hari itu dan aku harus berkemas untuk bepergian dan bergegas-gegas agar tidak ketinggalan pesawat. Aku kalang kabut. Anak-anak yang bisa mengendus keteganganku seperti ‘ikan hiu mengendus bau darah', mulai rewel, bertengkar, merengek-rengek untuk menarik perhatianku dan membuatku tak bisa membereskan apa-apa. Akhirnya, kesabaranku habis. Aku kehilangan kendali dan membentak mereka. Yah... aku berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pengasuh anak-anakku membuang muka, merasa tidak enak. Anak-anakku menangis. Aku mencoba mencium wajah mereka yang basah dengan air mata, mengucapkan selamat tinggal. Anak perempuanku mendorongku menjauh, anak laki-lakiku berdiri tegak, kaku dan marah sekali. Merasa frustasi, aku mengangkat bahu tak peduli. Aku ngebut ke bandara, menembus salju dan hujan yang dingin membeku.
memastikan pengasuh mereka datang hari itu dan aku harus berkemas untuk bepergian dan bergegas-gegas agar tidak ketinggalan pesawat. Aku kalang kabut. Anak-anak yang bisa mengendus keteganganku seperti ‘ikan hiu mengendus bau darah', mulai rewel, bertengkar, merengek-rengek untuk menarik perhatianku dan membuatku tak bisa membereskan apa-apa. Akhirnya, kesabaranku habis. Aku kehilangan kendali dan membentak mereka. Yah... aku berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pengasuh anak-anakku membuang muka, merasa tidak enak. Anak-anakku menangis. Aku mencoba mencium wajah mereka yang basah dengan air mata, mengucapkan selamat tinggal. Anak perempuanku mendorongku menjauh, anak laki-lakiku berdiri tegak, kaku dan marah sekali. Merasa frustasi, aku mengangkat bahu tak peduli. Aku ngebut ke bandara, menembus salju dan hujan yang dingin membeku.
Dengan marah dan gugup karena kuatir ketinggalan pesawat, aku menganalisa sikapku tadi dan membenarkannya. "Aku bekerja keras sekali untuk anak-anak itu! Apakah mereka menghargaiku? Tidak!" Hatiku sesak, aku kasihan sekali pada diriku sendiri.
Aku memarkir mobil kemudian menyeret koperku ke konter check in, bergegas ke gate lalu naik ke pesawat. Cuaca yang suram membuat hatiku semakin keruh. Suasana hatiku bercampur aduk antara marah karena merasa tindakanku benar, dan merasa bersalah karena telah membentak anak-anakku.
 Hal yang lebih buruk sudah menunggu. Pesawat yang kutumpangi sudah tua. Kami lepas landas menembus badai es yang mengamuk, meninggalkan Cleveland menuju Detroit. Di sana aku akan memberikan loka karya. Ketika pesawat naik menembus awan dan terguncang dalam arus udara yang tidak menentu, rasa bersalahku semakin besar. Bagaimana mungkin aku meninggalkan anak-anakku seperti tadi?
Hal yang lebih buruk sudah menunggu. Pesawat yang kutumpangi sudah tua. Kami lepas landas menembus badai es yang mengamuk, meninggalkan Cleveland menuju Detroit. Di sana aku akan memberikan loka karya. Ketika pesawat naik menembus awan dan terguncang dalam arus udara yang tidak menentu, rasa bersalahku semakin besar. Bagaimana mungkin aku meninggalkan anak-anakku seperti tadi?
Seorang pramugari berjalan di antara dua deretan kursi sambil membawa nampan penuh minuman ringan. Tiba-tiba terdengar bunyi berdebum keras; BUUMM!!!! Udara di dalam kabin sepertinya tersedot sepanjang lorong di antara deretan kursi, seperti pusaran angin puyuh. Masker oksigen terlontar dari tempat penyimpanannya di atas kepala penumpang dan terayun-ayun di depan kami seperti tangan pencabut nyawa. Sebuah pintu tiba-tiba lepas dan kami berada dalam suasana tegang. Pesawat berada kira-kira sebelas ribu kaki di atas danau Erie yang beku.
 Pesawat miring tajam lalu menukik dengan cepat. Aku memandang keluar jendela dan melihat permukaan beku danau Erie. Kami menukik tajam ke permukaan danau itu. Aku yakin, kami semua pasti mati. Aku mendongak dan melihat pramugari mencoba membuka pintu kokpit, tetapi pintu itu melengkung karena tekanan udara yang tersedot keluar sangat kuat. Intercom yang menghubungkan kabin dengan kokpit juga tidak berfungsi. Mereka tampak panik. Inilah saatnya, pikirku, aku pasti mati.
Pesawat miring tajam lalu menukik dengan cepat. Aku memandang keluar jendela dan melihat permukaan beku danau Erie. Kami menukik tajam ke permukaan danau itu. Aku yakin, kami semua pasti mati. Aku mendongak dan melihat pramugari mencoba membuka pintu kokpit, tetapi pintu itu melengkung karena tekanan udara yang tersedot keluar sangat kuat. Intercom yang menghubungkan kabin dengan kokpit juga tidak berfungsi. Mereka tampak panik. Inilah saatnya, pikirku, aku pasti mati.
Ketika itu, seluruh hidupku tidak melintas di benakku. Hanya ada dua pikiran di kepalaku. Pertama, karena aku belum meyiapkan surat wasiat, menurut hukum negara bagian Ohio anak-anakku akan kehilangan setengah hak warisan mereka. Kedua, kenangan terakhir mereka akan ayahnya adalah lelaki berwajah merah padam yang berteriak-teriak memarahi mereka. Aku sangat menyesal. Bagaimana mungkin aku meninggalkan mereka seperti tadi? Pikirku dengan penyesalan yang sangat dalam.
Aku mulai berdoa, sementara pesawat terus menukik dan semakin dekat ke permukaan Danau Erie. "Ya Tuhan," aku berdoa, "jika Engkau selamatkan kami semua, sekali ini saja, aku berjanji tidak akan meninggalkan rumah sambil marah-marah. Aku berjanji akan membuat anak-anakku selalu ingat bahwa aku sangat mencintai mereka dan bahwa mereka sangat berharga bagiku."
 Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak pintu pesawat tiba-tiba lepas sampai pesawat tiba-tiba terbang mendatar lagi -rasanya lama sekali- tetapi kejadiannya tepat ketika aku selesai berdoa. Aku tak tahu apakah aku berdoa dua puluh kali atau hanya sekali, tetapi aku yakin doaku dikabulkan.
Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak pintu pesawat tiba-tiba lepas sampai pesawat tiba-tiba terbang mendatar lagi -rasanya lama sekali- tetapi kejadiannya tepat ketika aku selesai berdoa. Aku tak tahu apakah aku berdoa dua puluh kali atau hanya sekali, tetapi aku yakin doaku dikabulkan.
Pesawat kami berputar lalu terbang kembali ke Cleveland. Kami semua turun lalu naik pesawat lain yang sejenis, yang membuat kami tetap cemas. Akhirnya kami mendarat di Detroit dan aku memberikan pelatihan di sana. Ironisnya, topik pelatihanku adalah "Mengatasi Stres." Sigmud Freud berpendapat, topik yang dapat kita ajarkan dengan sangat baik adalah topik yang sebenarnya harus kita pelajari. Hari itu, kata-katanya terbukti benar.
 Catatan akhir dari kisah ini adalah aku menepati janjiku. Ketika kembali ke Cleveland, hal pertama yang kulakukan adalah meminta maaf pada anak-anakku dan memeluk mereka erat-erat. Kemudian aku pergi ke notaris dan membuat surat wasiat. Sejak itu, sebelum meninggalkan rumah, meskipun hanya ke tempat kerja aku selalu mengungkapkan cintaku kepada anak-anakku. Sebelum melakukan perjalanan jauh dan lama, aku selalu mengucapkan kata perpisahan kepada mereka di ambang pintu. Kira-kira begini bunyinya, "Ayah ingin kalian tahu bahwa Ayah mencintai kalian, dan akan selalu mencintai kalian. Ayah selalu bangga dan bahagia menjadi ayah kalian. Kadang-kadang Ayah marah pada kalian karena perbuatan kalian, tetapi tak ada yang bisa membuat Ayah berhenti mencintai kalian!" Mendengar itu, biasanya mereka memutar-mutar bola mata mereka dan mendesah, seakan berkata, "Oh, haruskan kami mendengar pidato itu lagi?" kadang-kadang mereka menirukan aku dengan suara melengking, "Ya, ya, kalian tahu Ayah mencintai kalian dan akan selalu mencintai kalian..." Tetapi aku yakin, mereka suka mendengar kata-kataku. Suatu hari, aku berangkat tanpa mengucapkan pidatoku, aku lupa. Mereka menghubungi telepon mobilku dan berkata, "Ayah, katakan Ayah mencintai kami!"
Catatan akhir dari kisah ini adalah aku menepati janjiku. Ketika kembali ke Cleveland, hal pertama yang kulakukan adalah meminta maaf pada anak-anakku dan memeluk mereka erat-erat. Kemudian aku pergi ke notaris dan membuat surat wasiat. Sejak itu, sebelum meninggalkan rumah, meskipun hanya ke tempat kerja aku selalu mengungkapkan cintaku kepada anak-anakku. Sebelum melakukan perjalanan jauh dan lama, aku selalu mengucapkan kata perpisahan kepada mereka di ambang pintu. Kira-kira begini bunyinya, "Ayah ingin kalian tahu bahwa Ayah mencintai kalian, dan akan selalu mencintai kalian. Ayah selalu bangga dan bahagia menjadi ayah kalian. Kadang-kadang Ayah marah pada kalian karena perbuatan kalian, tetapi tak ada yang bisa membuat Ayah berhenti mencintai kalian!" Mendengar itu, biasanya mereka memutar-mutar bola mata mereka dan mendesah, seakan berkata, "Oh, haruskan kami mendengar pidato itu lagi?" kadang-kadang mereka menirukan aku dengan suara melengking, "Ya, ya, kalian tahu Ayah mencintai kalian dan akan selalu mencintai kalian..." Tetapi aku yakin, mereka suka mendengar kata-kataku. Suatu hari, aku berangkat tanpa mengucapkan pidatoku, aku lupa. Mereka menghubungi telepon mobilku dan berkata, "Ayah, katakan Ayah mencintai kami!"
 Pengalaman di pesawat mengajariku untuk menghargai hidupku dan hidup orang-orang lain di sekelilingku. Sekarang aku mengerti betapa berharga dan rapuhnya hidup ini dan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari.
Pengalaman di pesawat mengajariku untuk menghargai hidupku dan hidup orang-orang lain di sekelilingku. Sekarang aku mengerti betapa berharga dan rapuhnya hidup ini dan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari.
Mendiang ibuku selalu berkata, "Man proposes and God disposes" (Manusia berencana dan Tuhan menentukan). Tetapi sebenarnya ibuku lebih suka pepatah Yahudi yang lebih mengena, "Man plans and God Laughs" (Pria membuat rencana dan Tuhan tertawa).