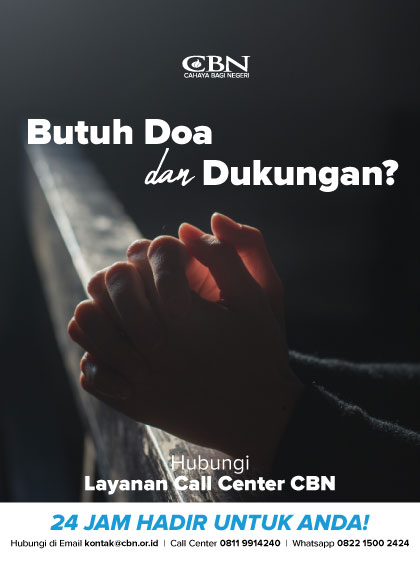Nasional / 1 January 2005
Popularitas dan Hadiah Untuk Hakim

Puji Astuti Official Writer
7042
Para hakim Indonesia dewasa ini berada dalam masyarakat yang oleh dunia dianggap sebagai salah satu masyarakat yang paling korup di dunia. Konteks sosial ini seyogianya harus senantiasa dipertimbangkan oleh setiap petinggi negara, termasuk petinggi hukum dalam membuat berbagai kebijakan dan putusan.
Korupsi yang begitu parah di Indonesia, jelas membutuhkan penanganan yang "superserius". Karena itu, tidak bisa ada peluang sesedikit apa pun yang dibuka bagi terjadinya perilaku korup, termasuk suap-menyuap dalam kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara.
 Berangkat dari apa yang telah dikemukakan di atas, tidaklah mengherankan kalau berbagai kalangan menelaah kritis apa yang disampaikan Ketua MA Bagir Manan, bahwa MA telah menyusun suatu kode etik perilaku hakim, yang membolehkan para hakim menerima "hadiah tertentu". Kebijakan itu dianggap sangat potensial untuk kemungkinan menimbulkan perilaku korup dan suap di kalangan hakim, meskipun tentu saja tidak dari awal direncanakan untuk itu.
Berangkat dari apa yang telah dikemukakan di atas, tidaklah mengherankan kalau berbagai kalangan menelaah kritis apa yang disampaikan Ketua MA Bagir Manan, bahwa MA telah menyusun suatu kode etik perilaku hakim, yang membolehkan para hakim menerima "hadiah tertentu". Kebijakan itu dianggap sangat potensial untuk kemungkinan menimbulkan perilaku korup dan suap di kalangan hakim, meskipun tentu saja tidak dari awal direncanakan untuk itu. Belum lagi, adanya Pasal 13 butir b UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menentukan kewenangan KPK untuk menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Pasal 16, 17, dan 18, mengatur tentang tatacara pelaporan dan penentuan status gratifikasi. Artinya apa?
Artinya, persoalan hadiah atau bahasa kerennya "gratifikasi" itu adalah sepenuhnya kewenangan KPK. Karena itu, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002, hanya KPK-lah yang memiliki kewenangan mengatur perincian hadiah apa yang boleh dan tidak boleh diterima oleh semua penyelenggara negara, termasuk para hakim.
Kode Etik
Kalau kita kaitkan dengan makna asas "lex superior derogat lege inferiori" yang berarti ketentuan yang lebih rendah tidak berlaku ketika ia bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dari sudut legal-normatif, maka tentu saja Kode Etik Perilaku Hakim yang dibuat Mahkamah Agung, tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, tanpa kekecualian, tetap harus tunduk pada berbagai asas hukum dan aturan hukum positif Indonesia. Mahkamah Agung tidak bisa melakukan kebijakan apa pun yang bersifat praeter legem (bertentangan dengan undang-undang).
Demikian juga jika kita menyoal tentang "kode etik perilaku hakim". Sejak adanya Komisi Yudisial, berdasarkan UU No 22 Tahun 2004, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, termasuk para hakim agung, diserahkan kepada Komisi Yudisial, yang diformulasikan dalam butir "b" bagian "Menimbang" dari UU No 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Lebih tegas lagi, Pasal 13 butir "b" UU No 22 Tahun 2004 menentukan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
 Secara logis, tentunya kita segera memahami, untuk mengimplementasikan kewenangan menjaga perilaku hakim, tentu saja Komisi Yudisial harus menyusun kode etik perilaku hakim, sehingga berdasarkan kode etik tersebut, Komisi Yudisial memiliki kriteria yang jelas dan standar tentang perilaku hakim yang menyimpang.
Secara logis, tentunya kita segera memahami, untuk mengimplementasikan kewenangan menjaga perilaku hakim, tentu saja Komisi Yudisial harus menyusun kode etik perilaku hakim, sehingga berdasarkan kode etik tersebut, Komisi Yudisial memiliki kriteria yang jelas dan standar tentang perilaku hakim yang menyimpang. Jadi sekali lagi, kewenangan untuk menyusun kode etik perilaku hakim sejak terbentuknya Komisi Yudisial, telah menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Dan, konon dalam Kode Etik Perilaku Hakim yang sementara disusun oleh Komisi Yudisial, "izin untuk menerima hadiah tertentu" itu tetap tidak dibenarkan. Dengan demikian, andaikata pun Mahkamah Agung ingin membuat kode etik perilaku hakim yang sifatnya internal, maka kode etik tersebut tidak boleh bertentangan, baik terhadap UU No 30/2002 tentang KPK maupun terhadap UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Akhirnya mudah-mudahan saja pernyataan Ketua MA yang sempat dimuat di berbagai media bahwa "hakim harus mencari popularitas", memang hanya suatu "salah ketik" belaka. Karena, kalau benar ada pernyataan demikian, berarti profesi hakim seolah-olah diidentikkan dengan para selebriti. Padahal, pada hakikatnya, profesi hakim memang adalah "profesi yang menyerupai orang yang kesepian". Hakim yang ideal, seyogianya membatasi bergaul terlalu luas, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusannya kelak.
Keteladanan yang sering ditampilkan para hakim yang arif di masa dahulu, adalah di saat kehujanan pun akan menolak tawaran bantuan sebuah payung, meski yang menawarkannya saat itu tidak terlibat dalam perkara yang sedang ditangani sang hakim itu. Itu hanya karena dikhawatirkan siapa tahu suatu waktu kelak si pemberi tawaran payung itu menjadi pihak yang berperkara, dan kebetulan sang hakim itulah yang mengadilinya. Subjektivitas dapat mempengaruhi putusannya.
Achmad Ali - Penulis adalah Guru Besar Ilmu Hukum
(nat) Sumber : Achmad Ali - www.suarapembaruan.com