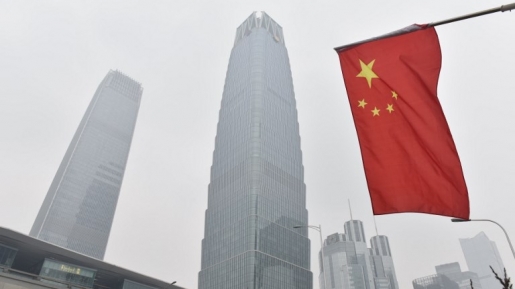Internasional / 4 July 2012
Kisah Gereja Pembantaian dan Rekonsiliasi di Rwanda (1)

daniel.tanamal Official Writer
Tidak semua gereja memiliki kisah dan latar belakang yang menyertai pembangunannya atau keberadaannya. Biasanya didominasi karena kebutuhan akan ibadah oleh masyarakat di suatu tempat tertentu. Namun ada beberapa gereja yang punya nilai lebih dari sekedar tempat untuk beribadah, seperti sebuah gereja di Rwanda, Afrika Tengah.
Negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen ini punya sejarah kelam mengenai perang saudara yang mengakibatkan genosida dan pembantaian etnis terjadi. Tercatat sekitar 800.000 nyawa etnis Tutsi dan etnis lainnya menjadi korban atas kepentingan kelompok politik yang ingin menguasai pemerintahan. Hal itu terjadi selama kurun 100 hari sepanjang 6 April hingga 15 Juli 1994.
Disitulah terdapat Gereja Katolik Ntarama, bangunan suci umat Kristen yang masih berdiri dengan tembok bata merah yang mulai rapuh dimana-mana. Gereja yang menjadi saksi bisu dimana pembantaian dan kejahatan manusia terjadi. Gereja yang kini menjadi situs sejarah sebagai penghormatan terhadap para korban itu terkenal dengan kengeriannya, karena memuat tumpukan tengkorak dan tulang belulang, berikut dengan pakaian yang kotor penuh jelaga dan debu milik para korban, yang mereka pakai di hari pembantaian.
Ternyata gereja tersebut pernah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para warga, karena sebelum tahun 1994, tidak ada tentara yang berani menyerang gereja. Namun hal itu segera berubah, ketika militan etnis Hutu Interahamwe melakukan serangan frontal dan mematikan dengan menghujani gereja dengan peluru tajam. Siapapun yang ditemu diluar gereja, mulai bayi hingga orangtua, baik lelaki maupun perempuan akan menghadapi ajalnya dengan tebasan parang.
Hal inilah yang diingat kembali oleh kurator dari gereja berumur 26 tahun itu, Valentine Ndamage yang selamat dari pembantaian itu karena ia dan keluarganya tinggal di Kongo dan baru tinggal di Rwanda, setahun setelah masa kelam itu berakhir. "Saya masih mengingat mayat-mayat yang bergelimpangan di Gisenyi," katanya mengenang peristiwa yang dibeberapa dekade kemudian menjadi tali pengikat dan rekonsiliasi diantara korban dan pelaku untuk berdamai dan mulai memikirkan Rwanda yang berjuang bagkit dari kekelaman (bersambung).